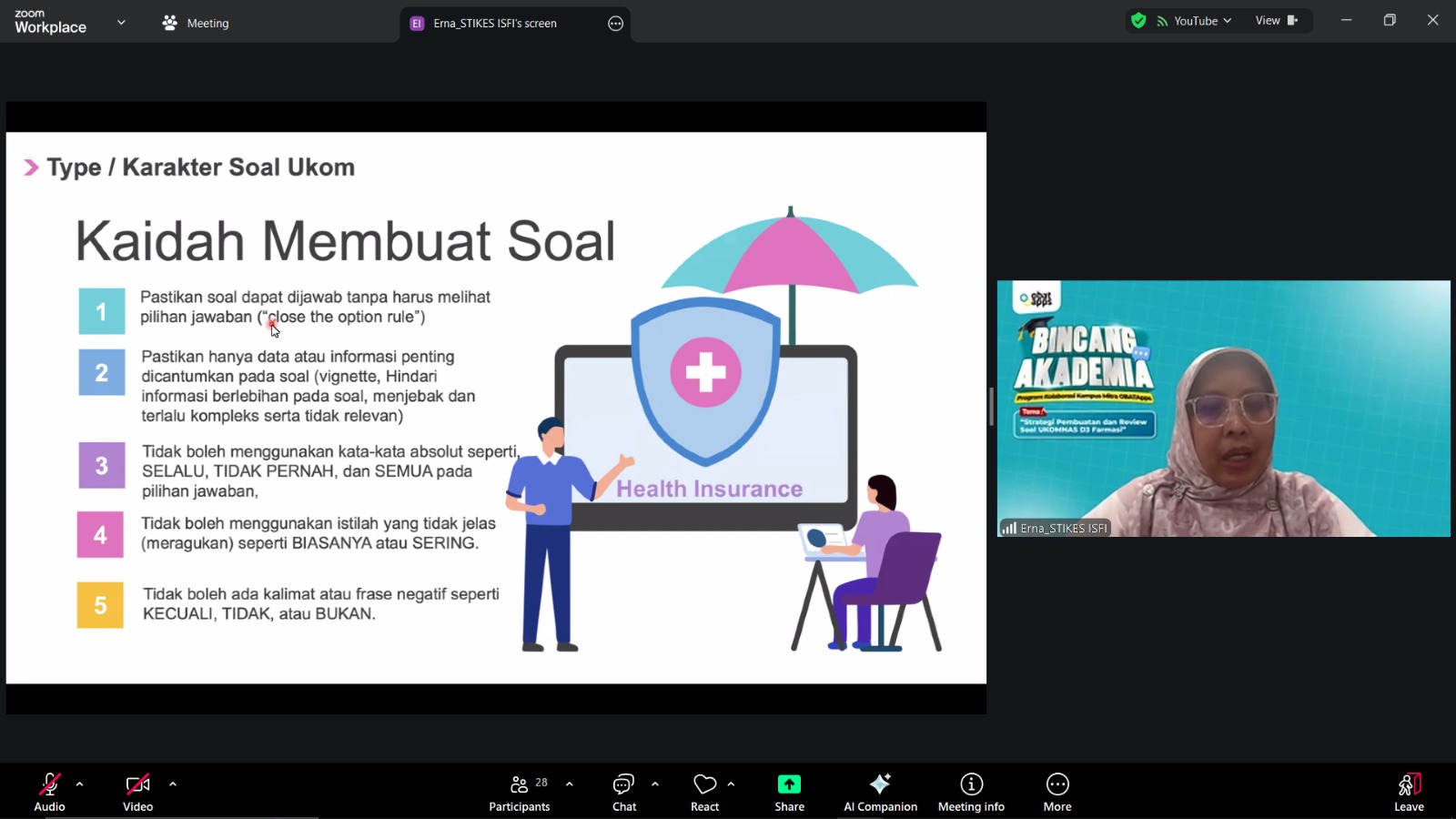Banjarmasin | OPINI. Hari Ibu 22 Desember 2025, kembali mengetuk kesadaran kita. Ia datang bukan sekadar sebagai tanggal dalam kalender, bukan pula hanya perayaan seremonial dengan bunga dan ucapan manis di media sosial. Hari Ibu adalah momen hening—saat kita diajak menunduk, menengok ke dalam diri, dan bertanya dengan jujur: sejauh apa kita telah memaknai peran seorang ibu dalam hidup, dalam bangsa, dan dalam kemanusiaan?
Bagi seorang anak bangsa, ibu adalah fondasi pertama dari Indonesia itu sendiri. Dari rahim para ibu, lahir generasi yang kelak mengisi ruang-ruang sejarah: menjadi petani yang setia pada tanahnya, guru yang sabar di ruang kelas, nakes yang setia di bangsal sunyi, hingga pemimpin yang berdiri di podium kekuasaan. Namun jauh sebelum semua peran itu disematkan, ibu telah lebih dulu mengajarkan arti kejujuran, ketekunan, dan keberanian—bukan lewat pidato, melainkan lewat teladan hidup. Bangsa yang besar bukan hanya dibangun oleh gedung tinggi dan jalan tol panjang, tetapi oleh nilai-nilai yang ditanamkan seorang ibu di meja makan sederhana, di sela-sela doa, dan dalam pelukan yang menenangkan.
Sebagai akademisi, Hari Ibu seharusnya menjadi cermin refleksi yang lebih dalam. Kita sering berbicara tentang kualitas sumber daya manusia, tentang bonus demografi, tentang daya saing global. Namun kerap lupa bahwa pendidikan paling fundamental tidak dimulai di kampus ternama, melainkan di rumah—bersama seorang ibu yang mungkin tak pernah menulis jurnal ilmiah, tetapi meneliti kehidupan dengan kepekaan hati. Ibu adalah kurikulum pertama, dosen pertama, dan evaluator paling jujur dalam hidup kita. Ia mengajarkan etika sebelum logika, empati sebelum prestasi, dan tanggung jawab sebelum ambisi. Dalam dunia akademik yang kadang terjebak pada angka dan peringkat, ibu mengingatkan kita bahwa esensi ilmu adalah memanusiakan manusia.
Hari Ibu juga mengajak kita, sebagai bagian dari umat manusia, untuk melihat ibu melampaui batas-batas biologis dan geografis. Di berbagai belahan dunia, ibu menghadapi tantangan yang berbeda, namun luka dan harapannya sering kali sama. Ada ibu yang membesarkan anak di tengah konflik, ada yang berjuang di tengah kemiskinan, ada pula yang menua dalam kesepian. Di titik inilah Hari Ibu menjadi panggilan nurani global: bahwa keadilan sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap perempuan bukan sekadar isu kebijakan, melainkan soal kemanusiaan paling mendasar. Cara kita memperlakukan para ibu hari ini akan menentukan wajah peradaban esok hari.
Namun memaknai Hari Ibu tidak cukup dengan nostalgia dan puisi atau dengan berpakaian kebaya. Ia menuntut keberanian untuk bertindak. Menghormati ibu berarti memastikan akses pendidikan yang adil bagi perempuan, layanan kesehatan yang layak bagi ibu dan anak, serta ruang aman bagi perempuan untuk tumbuh dan berdaya. Menghormati ibu berarti menata kebijakan publik dengan empati, menyusun riset dengan keberpihakan, dan mengambil keputusan—sekecil apa pun—dengan kesadaran akan dampaknya bagi kehidupan keluarga.
Di Hari Ibu 2025 ini, barangkali yang paling kita butuhkan adalah kejujuran untuk mengakui satu hal sederhana: bahwa kita ada karena pengorbanan yang sering tak terlihat. Ibu mungkin tak selalu benar, tetapi cintanya hampir selalu utuh. Ia mungkin tak selalu kuat, tetapi doanya jarang putus. Dan sering kali, ketika dunia terasa terlalu bising, nama “ibu” adalah satu-satunya kata yang sanggup menenangkan.
Hari Ibu bukan tentang mengagungkan masa lalu, melainkan menata masa depan. Masa depan bangsa, masa depan ilmu pengetahuan, dan masa depan kemanusiaan. Jika kita sungguh ingin dunia yang lebih adil, lebih beradab, dan lebih manusiawi, maka mulailah dari satu hal yang paling dekat: memuliakan ibu—dalam pikiran, dalam kebijakan, dan dalam tindakan nyata. Karena pada akhirnya, cara kita memaknai ibu adalah cara kita memaknai kehidupan itu sendiri. Selamat Hari Ibu | Kayutangi, Awal Rajab 1447, yugs2025.